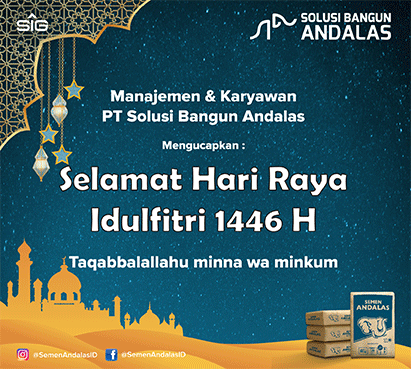Mewaspadai Fenomena Childfree

Oleh Mifta Rizki Mardika, S.I.Kom
Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.
MOMENTUM--Childfree, istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan generasi muda. Terlebih saat ini generasi Z dan generasi milineal tengah memimpin jumlah populasi di Indonesia dengan jumlah lebih dari 20 persen.
Perlunya mewaspadai fenomena ini dikarenakan pengaruhnya terhadap kemungkinan penurunan angka kelahiran total atau TFR (total fertility rate) dan sederet pro-kontra didalamnya. Peran serta teknologi digital yang semakin maju juga memiliki andil dalam proses penyebaran isu terkait chidfree.
Namun, apakah fenomena ini sepenuhnya hanya terkait dengan hak-hak pribadi dalam memilih pilihan hidup, mengedepankan kebebasan untuk berkehidupan yang bahagia tanpa anak atau dapat berdampak besar pada kehidupan sosial bahkan bernegara?
Beberapa waktu belakangan ini, media sosial tengah diramaikan dengan trend childfree yang mulai di suarakan oleh para influencer dan youtuber ibu kota. Sebut saja Gita Savitri yang secara terbuka mengungkapkan ketidakinginan dirinya dan suami untuk memiliki anak.
Childfree memiliki pengertian sebagai pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang menjalani kehidupan pernikahan atau tidak, dengan tidak ingin melahirkan atau memiliki anak.
Walaupun memang pada hakikatnya keputusan untuk memiliki anak bagi pasangan adalah hak setiap masing-masing individu. Namun bisa dibayangkan apabila banyak orang-orang yang berpikir seperti Gita jumlahnya berlipat ganda.
Terlebih, pengaruh media sosial yang semakin membawa tren dan isu ini kepermukaan dengan sangat cepat. Jika diumpamakan 50 persen saja pasangan suami-istri di Indonesia mengikuti jejak Gita dengan memilih keputusan tidak memiliki anak.
Maka akan jelas agregat keputusan tersebut berdampak pada kondisi sosial-ekonomi-demografi negara.
 Gita Savitri dan Suami. Sumber: Instagram pribadi Gita Savitri (@gitasav)
Gita Savitri dan Suami. Sumber: Instagram pribadi Gita Savitri (@gitasav)
Alasan seseorang untuk tidak memiliki anak muncul dari banyak faktor seperti alasan pribadi, psikologis, ekonomi, lingkungan sosial, filosofis, fobia, orientasi seksual dan lain sebagainya.
Survei yang dilakukan penulis buku Childlesness in United States, Tomas Sobotka menunjukkan kekhawatiran terhadap overpopulasi sebagai salah satu alasan paling umum kenapa seseorang memilih childfree.
Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar, dalam data yang dipublikasi oleh Worldometer pada tahun 2021 sudah terdapat 7,85 miliar manusia yang menjadi penduduk dunia saat ini.
Hal ini jauh meningkat pesat daripada data yang pertama kali dikemukakan terkait jumlah penduduk dunia yang hanya berjumlah 125.000 pada satu juta tahun yang lalu, kemudian tercatat pula pada saat berdirinya PBB jumlah penduduk dunia hanya sejumlah 2,6 miliar, kemudian bertambah menjadi 5 miliar pada 1987, kemudian 6 miliar pada tahun 1999.
Di Indonesia sendiri, pertumbuhan penduduk terjadi sangat drastis, dimana kini Indonesia menempati posisi negara dengan populasi terbanyak nomor empat dunia. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia hanya sebanyak 119,20 juta, kemudian pada tahun 1990 179,38 juta, dan pada tahun 2020 sejumlah 270,20 juta. Hal ini yang membuat pulau jawa menjadi pulau dengan penduduk terpadat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 141 juta jiwa.
Tentu amat berbahaya apabila kepadatan penduduk tersebut tidak dapat terkontrol dengan baik, hal-hal buruk seperti inflasi, polusi, kelaparan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya akan terjadi akibat dari meledaknya jumlah populasi.
Sebelum adanya fenomena childfree, sudah banyak negara yang memberlakukan kebijakan untuk menekan angka kelahiran. Salah satu kebijakan yang pernah diterapkan oleh negara dengan penduduk paling padat dunia adalah kebijakan pemerintah Deng Xiaoping di Negara Cina pada tahun 1979 melalui kebijakan yang dinamakan one-child policy dan akhirnya dihapuskan pada 29 Oktober 2015.
Kebijakan ini diawali kekhawatiran pemerintah China akan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan karena tidak mampu menahan ledakan populasi yang terjadi, Presiden Deng Xiaoping, menerapkan kebijakan “One Child Policy” yaitu kebijakan yang mewajibkan satu keluarga hanya diizinkan untuk mempunyai satu anak saja.
Namun kebijakan itu kemudian memunculkan masalah baru, yakni angka aborsi dan sterilisasi perempuan meningkat drastis, terjadi ketidakseimbangan gender karena jumlah laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Ketidakseimbangan ini terjadi karena pasangan suami-istri semasa kebijakan one-child policy diberlakukan, cenderung ingin memiliki anak laki-laki agar kelak dapat bekerja, sehingga anak perempuan yang sudah terlanjur lahir akan ditelantarkan, dibiarkan diadopsi secara ilegal atau bahkan dibunuh.
Selain itu, jumlah penduduk lansia meningkat drastis yang membuat pensiunan angkatan kerja semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang seharusnya berada di masa sekolah justru memasuki pasar tenaga kerja.
Dari kasus kebijakan di China ternyata pada penerapannya, pembatasan angka kelahiran banyak memberikan efek dan masalah juga. Walaupun pada hakikat awal mulanya bertujuan untuk menekan populasi guna mensejahterakan pembangunan dan ekonomi. Namun nyatanya mampu mempengaruhi tingkat demografi negara, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
Masalah demografi dimana adanya kesenjangan kelompok usia produktif dan usia tua dibanding dengan populasi dunia yang diakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk bereproduksi, tidak hanya dirasakan oleh negara China.
Bahkan kini negara Rusia, Jepang, Jerman dan Singapura memberlakukan pemberian sejumlah tunjangan, hadiah bahkan kompensasi libur dan hari tua bagi siapapun yang ingin mempunyai anak.
Seperti hal nya yang dilakukan pemerintah Singapura, Singapura membuat kampanye baru "Miliki Tiga Anak Atau Lebih Jika Anda Mampu." dan mendesak warganya untuk bisa punya tiga anak atau lebih.
Salah satu cara Singapura untuk menyukseskan kampanye ini adalah membuat program "perahu cinta" bagi pasangan yang ingin memiliki momongan. Pada program ini, pasangan akan diberikan pendidikan khusus seputar kesuburan dan seksual di sebuah penginapan khusus suami istri. Dan pemerintah akan memberikan kompensasi untuk setiap anak pertama atau kedua yang lahir dari program tersebut, dengan memberikan uang pada orangtuanya sebesar US$8.000 (Rp109 juta), atau US$10 ribu (Rp136 juta) bagi anak ketiga atau seterusnya.
Hal serupa juga terjadi di Jepang. Dikutip dari sebuah laporan Japan Times Mei 2021, Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Data pemerintah Jepang di bulan Mei juga menunjukkan bahwa perkiraan populasi anak-anak Jepang telah menyentuh titik terendah setelah melandai selama 40 tahun berturut-turut hal ini dipercaya akibat trend childfree yang menjadi suatu hal ‘biasa’ bagi warga Jepang.
Untuk itu pemerintah Jepang memberikan sejumlah insentif bagi para warganya untuk bisa memiliki anak dengan harapan hidup yang tinggi, antara lain dengan cara memberikan dukungan dana pernikahan, dukungan dana kesehatan, santunan dana melahirkan, dana tunjangan anak, pemberian cuti melahirkan dan mengurus anak serta menambah fasilitas penitipan anak.
Di Indonesia sendiri telah digalakkan kampanye program ‘Keluarga Berencana’ atau KB yang diatur dalam UU N0 10 tahun 1992, program ini kemudian dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Slogan “dua anak cukup atau dua anak lebih baik” kini masih diteruskan guna terus menurunkan angka TFR. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Indonesia nyatanya memang mengalami penurunan sejak tahun 1991. Pada akhir tahun 1991, angka kelahiran total tercatat mencapai tiga persen.
Catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi (alat KB) dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66 persen hingga 2017 silam.
Namun meski angka total kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh BKBBN belum mencapai sasaran Renstra (Rencana Strategis) yang bertujuan untuk menurunkan TFR hingga 2,28 anak per wanita.
Lantas bagaimana jika trend childfree semakin mengemuka di Indonesia? Walaupun pemerintah punya agenda besar untuk menurunkan angka TFR dan childfree memiliki keunggulan untuk ambil bagian menekan angka kelahiran, namun besar harapan agar jangan sampai ‘kebablasan’ hingga memunculkan ancaman demografi di Indonesia. Kondisi penduduk usia tua yang jumlahnya semakin mendominasi. Hal ini akan berpengaruh pada struktur penduduk di Indonesia.
Kondisi tersebut juga akan berdampak pada rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).
Seperti Jepang, Rusia dan Jerman, kemungkinan Indonesia akan mengalami kesulitan untuk menaikkan angka kelahiran total manakala jumlah kelahiran yang terlampau sedikit. Terlepas dari kebijakan KB yang berlaku, keluhan sebagian penganut childfree bahwa beban ekonomi membesarkan anak sangatlah besar, menjadi suatu realita.
Meskipun kini biaya kelahiran dapat ditanggung BPJS, namun perawatan dan membesarkan anak dengan ‘layak’ akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada sisi lain, orang tua mereka berhadapan dengan tekanan upah minim, persaingan dunia kerja yang semakin menggila, kebutuhan akan pendidikan dan lain sebagainya membuat ‘calon orang tua’ berfikir ulang untuk memiliki anak. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu kritik bagi pemerintah.
Pemerintah harus sadar bahwa ada peranan negara di sana, yang tidak hanya mengendalikan jumlah kelahirannya, melainkan juga dapat memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkan memiliki seperangkat jaminan untuk dapat hidup layak sebagaimana mestinya.
Negara juga harus memastikan bahwa para lansia tidak lagi menjadi beban bagi sang anak, karena mereka telah dipelihara oleh negara. Salah satu contohnya, jaminan anak bisa dilakukan dengan memberikan fasilitas dan jaminan kesejahteraan bagi setiap anak yang dilahirkan, lewat KIA (Kartu Identitas Anak).
Jadi pemanfaatan kartu tersebut tidak hanya sebagai salah satu syarat administrasi kependudukan negara di Indonesia, atau hanya sebagai skema insentif, yaitu bahwa anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan diskon kala berbelanja atau saat memasuki taman-taman hiburan seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah. Namun juga dapat dikembangkan ke arah ‘soft requirement’ untuk pendidikan secara gratis, yang secara tidak langsung melakukan jaminan pada pendidikan anak.
Dalam konteks dunia digital, pemerintah dapat memanfaatkan kecepatan dan kehandalan teknologi digital untuk bisa terjun kepada program-program kampanye digital. Melalui media - media sosial yang kekinian dalam penyampaian informasi, diharapkan pesan itu langsung sampai tepat ke sasaran yang diinginkan yaitu generasi z dan milenial dengan mudah, efektif dan cepat.
Seperti pemanfaatan media sosial instagram atau twitter dari instansi pemerintah guna melancarkan berbagai program misalnya kampanye KB digital ataupun memperbanyak edukasi mengenai reproduksi, pilihan childfree, parenting dan lain sebagainya melalui konten-konten video kreatif agar lebih menarik dan massif. (*)

Mifta Rizki Mardika, S.I.Kom
Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.
Editor: M Furqon
Editor: Harian Momentum