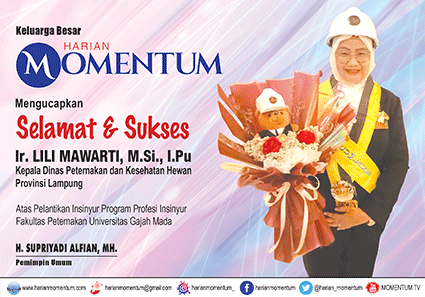Mafia dan Dampak Sosial Konflik Tanah
MOMENTUM--Sinar matahari sedang pada puncak sengatnya ketika ratusan massa berdemonstrasi di salah satu kantor pemerintah kabupaten yang mengurus pertanahan, beberapa waktu lalu. Mobil komando yang berisi seperangkat alat pelantang suara ukuran besar berhasil memasuki halaman kantor. Massa ikut merangsek bersama teriakan, spanduk, dan karton-karton bertuliskan aneka tuntutan.
Dari atas mobil komando, orasi terus berganti-ganti. Sementara, beberapa orang tokoh dipersilakan masuk ruang kantor untuk berdialog menyampaikan keinginannya. Massa terjemur hampir satu jam, tetapi perunding di dalam kantor tak kunjung selesai. Hal ini membuat orator semakin jalang dan meneriakkan tuntutannya.
Panas terik membuat massa dengan aneka atribut bermandi peluh. Lalu, satu persatu mulai meninggalkan gelanggang mencari perlindungan teduh di garasi parkir mobil, di kebun, di emperan rumah, dan apa saja yang bisa meneduhi. Massa di halaman tinggal sebaris, demo sudah hampir sampai puncaknya. Tak pelak, orator memanggil dengan keras para peserta demo untuk kembali turun. Mereka dengan sisa tenaganya merapat dan berdorong-dorongan dengan polisi yang menjaga.
Ilustrasi drama demonstrasi diatas adalah fakta lapangan saat ini ketika sekelompok orang ingin menyampaikan aspirasinya. Salah satu yang masih hangat di Lampung saat ini adalah kisruh pengakuan atau klaim dari sekelompok orang yang ingin menguasai tanah milik salah satu perusahaan BUMN yang masih aktif diusahakan. Ini menjadi preseden yang membawa masalah vertikal dan horisontal dan berpotensikonflik sosial di masyarakat.
Tulisan ini bukan membahas kasus ini, tetapi ingin berupaya membedah apa yang sesungguhnya terjadi pada konflik tanah atau agraria yang terus terjadi ini. Apakah massa yang berteriak-teriak sampai kehabisan suara, berkeringat, dan berhadap-hadapan dengan aparat keamanan sambil membentangkan karton-karton bertuliskan hujatan itu tahu persis dengan duduk persoalannya? Dan, apa risiko dari upaya-upaya model paksa ini bagi stabilitas nasional?
Sebelum membahas lebih dalam, kita wajib pahami tentang konstruksi fakta fenomena sosial yang saat ini terjadi di negeri ini. Bahwa, hampir semua persoalan bangsa yang buntu di meja mediasi banyak sekali yang ditempuh dengan pengerahan massa. Padahal, kondisi saat ini yang namanya tenaga dan waktu, terlebih bagi masyarakat awam, sangat berharga. Seorang buruh, misalnya, jika tidak bekerja sehari saja, maka terpotong penghasilannya. Dan, itu sudah sangat disadari oleh semua lapisan; “tidak ada gerak kalau tidak ada ulak”.
Atmosfer pengerahan massa model pragmatis ini baru sebatas asumsi penulis. Tetapi, beberapa data dan fakta mengarah kepada penguatan hipotesis ini. Yakni, ketika di lapangan bertanya kepada beberapa orang pengikut massa dengan satu pertanyaan yang sama. Yakni, “Apakah Anda tahu duduk persoalan tanah yang dituntut demonstran?” Dan, jawaban mereka hampir sama “katanya soal tanah punya adat!”. Jawabannya sebatas itu.
Cukup menarik disimak, dari beberapa spanduk dan pamflet-pamflet yang dibentangkan, ada yang bertulis “Berantas Mafia Tanah!” Kalimat ini menjadi kontradiksi dengan asumsi yang mengarah kepada hipotesis bahwa massa itu bisa bergerak karena digerakkan oleh sutradara. Sutradara menjadi kata ganti untuk menghaluskan istilah mafioso alias jaringan mafia.
Tak hendak pula masuk ke persoalan siapa menggerakkan siapa dan untuk kepentingan siapa, kita patut waspada dengan efek sosial dari model “berunding maksa” ini.
Sebab, kalau terjadi apa-apa, semisal gesekan dan benturan massa dengan aparat atau dengan massa lawan, yang menjadi korban adalah rakyat biasa yang nota bene tidak tahu apa-apa. Lebih dalam lagi, mereka ternyata adalah saudara kita juga yang senasib.
Fenomena ini bisa memicu konflik sosial lebih parah ketika mereka kembali ke masyarakat. Warga dari desa yang sama bisa terbelah dalam kubu-kubu yang berhadap-hadapan. Ini sangat rawan dan berpotensi mengganggu psikologi massa dan bisa turun-temurun.
Secara etimologis "konflik" berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian, baik itu antar pribadi, pribadi dan kelompok, maupun antar kelompok.
Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam proses perebutan sumber daya dalam kemasyarakatan. Baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Salah satu konflik yang masih krusial di Indonesia adalah konflik agraria ini.
Tentunya banyak dampak sosial yang diterima masyarakat sekitar area konflik. Mulai dari ketidakamanan di sekitar tempat tinggal hingga kehilangan nyawa. Masyarakat yang tinggal di daerah konflik akan merasakan was-was dalam melakukan segala aktivitasnya. Suasana mencekam itu terus berlangsung selama konflik belum terselesaikan, bahkan jika terjadi bentrok antar kelompok dapat menyebabkan kericuhan.
Dampak terburuknya adalah terdapat korban jiwa akibat konflik yang dilakukan dengan protes secara brutal tanpa memikirkan nyawa seseorang, meski dari kelompoknya sendiri. Selain itu, dampak kehilangan pekerjaan bagi beberapa masyarakat yang bekerja pada perusahaan atau perkebunan yang terlibat konflik.
Kesulitan untuk melakukan aktivitas dapat menghambat para pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan otomatis kehilangan penghasilan para pekerja sekitar konflik membutut pada kemiskinan perekonomian. Konflik yang terjadi juga seringkali merusak fasilitas dan lingkungan, bentrok akibat konflik dengan mengobrak-abrik daerah sekitar berdampak pada kerugian, baik kerugian bagi masyarakat sekitar mau pun kerugian perusahaan.
Dalam konteks ini, konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dan secara hukum dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat mulai dari ketegangan sosial, kerugian secara ekonomi, kerusakan lingkungan, bahkan perampasan HAM.
Oleh karena itu, ketika suatu konflik yang melibatkan massa terjadi, opsi terbaik adalah segera menyelesaikan dengan arif dan bijaksana melalui musyawarah untuk mufakat. Jika parapihak tidak mendapatkan titik temu, sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum, jalur legalnya adalah ke Pengadilan. Dan pengerahan massa adalah opsi yang legal tetapi terlalu besar pengorbanannya.
Tentang konflik agraria yang masih terus terjadi di Indonesia, Pakar Hukum Tanah Fakultas Hukum UGM Prof. Nurhasan Ismail dalam yang telah tayang di https://ugm.ac.id mengatakan, selain memang masih rawan masalah juga karena masih ada oknum-oknum yang memobilisasi. Dalam bahasa umum, oknum-oknum ini biasa disebut mafia tanah.
Menurut Nurhasan mafia tanah merupakan jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisasi, sangat rapi, sistematis, tampak wajar, dan legal. Namun, di dalamnya tetap terkandung tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain.
Fakta ada dan berlangsungnya mafia tanah dapat dirujuk pada data pada bulan Februari 2020 yaitu Kementerian ATR BPN menengarai dan memproses 61 sengketa tanah yang melibatkan mafia tanah.Dan pada kesempatan yang sama Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan sejumlah orang anggota Mafia Tanah sebagai tersangka.
Mafia Tanah sebagai kelompok yang terstruktur dan terorganisir, terstruktur karena kelompok mafia tanah mempunyai struktur organisasi dengan melibatkan banyak aktor dan pembagian kerja yang sistematis dengan susunan. Ada kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya memengaruhi kebijakan dan memengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan.
Ada juga kelompok Garda yang berfungsi sebagai aktor yang berjuang secara legal (warga masyarakat biasa) dan illegal (preman dan Pengamanan Swakarsa).
Ada pula kelompok profesi yang berwenang yang terdiri dari para oknum advokat, Notaris-PPAT, okum pejabat pemerintah dari pusat – daerah yang berfungsi sebagai pendukung baik legal dan ilegal.
Sementara itu, disebut terorganisir karena mafia tanah menggunakan berbagai metode kerja yang keras-ilegal. Yaitu dengan tindakan perebutan tanah dan pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran, dan melakukan konflik dengan menggunakan kekerasan yang berpotensi taruhan nyawa.
Sedangkan cara halus-ilmiah dan tampak legal, adalah upaya pencarian dokumen kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen kepemilikan tanah dengan tampilan hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan aslinya. Proses pendekatan dalam rangka negosiasi dengan pemilik tanah, serta melakukan pengajuan gugatan dengan logika berpikir yang sistematis dan logis. (*)
Oleh: Fitria Adinda, Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila
Editor: Agus Setyawan